
Oleh Eben E. Siadari *
JAKARTA, KalderaNews.com — “Manusia tidak hidup dari roti saja.” Man shall not live on bread alone. Mungkin kamu sudah akrab dengan kalimat ini. Ia kerap dipakai untuk menekankan hidup bukan hanya tentang hal-hal yang bersifat material. Ia juga tentang yang nonmaterial.
Di antara yang nonmaterial itu adalah kata-kata. Manusia tidak dapat hidup tanpa kata-kata. Setiap hari kita mendengar, berbicara, membaca dan merenung dengan dan oleh kata-kata.
Guru, dosen, mengajar dengan kata-kata. Ibu, ayah, memberi nasihat dengan kata-kata. Kamu menjelaskan dan mempresentasikan gagasan menggunakan kata-kata.
Boleh percaya boleh tidak, kata-kata itu punya tenaga. Ia membawa energi. Kata-kata yang ditata dengan baik, ia akan membawa tenaga yang baik dan membangun. Namun, kata-kata dapat melemahkan bila ia tidak diolah dengan benar.
Bisa jadi kamu mengira urusan tata dan olah kata semacam ini penting saat berkhotbah atau mengajar. Betul, tetapi tidak hanya itu. Olah dan tata kata juga penting dalam mengkomunikasikan kepedulian, cinta, pertolongan kepada yang lemah. Dalam hal ini kaum yang termarginalkan.



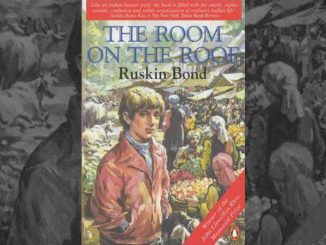

Leave a Reply